“Film seperti
ini kok bisa lolos sensor? Film begini merusak moral anak-anak! Mau dibawa ke
mana anak-anak kita kalau dikasih tontonan seperti itu?”
Beberapa waktu lalu saya
hanya bisa geleng-geleng kepala ketika banyak orangtua memprotes film ini dan
itu, sinetron ini dan itu.
Ah, bukannya saya setuju
pada tayangan berisi pergaulan bebas, kekerasan, dan hedonis yang merusak
moral.
Tidak, saya tidak setuju dengan tayangan seperti itu. Yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah karena sebagian yang memprotes itu tidak melihat situasinya terlebih dahulu.
Tidak, saya tidak setuju dengan tayangan seperti itu. Yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah karena sebagian yang memprotes itu tidak melihat situasinya terlebih dahulu.
“Anak saya yang kecil jadi
penakut setelah nonton Conjuring. Gimana sih, kok film yang begitu boleh
diputar di bioskop? Nakut-nakutin anak balita aja!”
Melihat ada yang salah di
sini? Yang bikin saya geleng-geleng kepala?
Yup. Conjuring bukan film untuk anak balita. Kalau saja si ibu tersebut
menerapkan budaya sensor mandiri, tentu tak perlu ada kejadian anak balitanya menjadi
penakut setelah menonton film.
Sayangnya, si ibu justru mengajak anak kecilnya itu menonton film yang bukan untuk usianya.
Sayangnya, si ibu justru mengajak anak kecilnya itu menonton film yang bukan untuk usianya.
Mengenal Budaya Sensor Mandiri
Apa itu budaya sensor
mandiri? Bukankah sudah ada Lembaga Sensor Film (LSF) yang berkewajiban
menyensor film-film yang akan ditayangkan di bioskop dan TV? Kenapa perlu ada budaya sensor mandiri dalam keluarega sendiri?
Dalam roadblog di Bandung
tanggal 14 Mei 2015, Dody Budiatman dari LSF RI menyebutkan bahwa budaya sensor
mandiri adalah sensor yang dilakukan oleh masyarakat.
 |
| Wakil Ketua LSF, Dody Budiatman, mengingatkan pentingnya membangun budaya sensor mandiri. |
LSF tentu saja tetap
melakukan penyensoran terhadap materi tontonan yang akan dikonsumsi oleh
publik. Unsur kekerasan, perjudian, narkoba, pornografi, pelecehan terhadap
suatu agama, dan pertentangan antarsuku atau SARA akan digunting oleh LSF.
Dalam kesempatan berbeda, Ahmad
Yani Basuki mengatakan bahwa kategori tayangan telah ditentukan oleh LSF. Ada
yang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak, ada pula yang diperuntukkan bagi
remaja.
Ketua LSF ini mengingatkan bahwa setelah sebuah tayangan lolos dari sensor LSF, masyarakatlah yang harus melakukan sensor secara mandiri pada tayangan di bioskop dan di televisi. 1)
Ketua LSF ini mengingatkan bahwa setelah sebuah tayangan lolos dari sensor LSF, masyarakatlah yang harus melakukan sensor secara mandiri pada tayangan di bioskop dan di televisi. 1)
Melakukan sensor mandiri
ini bukan dengan cara menggrebek apalagi melakukan tindakan anarkis pada
bioskop atau stasiun TV yang menayangkan film.
Sensor mandiri ini berupa perilaku selektif dalam memilih film atau tayangan yang akan ditonton. Lalu, siapa saja yang diharapkan berperan aktif melakukan sensor mandiri?
Sensor mandiri ini berupa perilaku selektif dalam memilih film atau tayangan yang akan ditonton. Lalu, siapa saja yang diharapkan berperan aktif melakukan sensor mandiri?
Wakil Ketua LSF Dody Budiatman dalam roadblog di Bandung menyebutkan tiga komponen yang harus aktif menyensor tayangan secara mandiri.
1. Masyarakat perfilman.
Masyarakat perfilman diharapkan membuat film
sesuai dengan undang-undang yang ada. Jangan membuat tontonan yang membenturkan
konflik-konflik sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
2. Masyarakat penonton.
Termasuk masyarakat penonton dalam budaya
sensor mandiri ini adalah orangtua dan institusi pendidikan. Orangtua yang memperhatikan
klasifikasi film tentu tidak akan membawa anak-anak menonton film yang bukan
untuk konsumsi mereka.
3. Pemilik gedung bioskop.
Pemilik gedung bioskop juga dituntut membudayakan
sensor mandiri ini. Misalnya dengan tidak menayangkan trailer film berklasifikasi
17+ pada saat penayangan film untuk anak-anak.
Budaya Sensor Mandiri dalam Keseharian
Sebagai orangtua, kita
tidak bisa berlepas tangan dari urusan sensor-menyensor ini. Menonton film di
bioskop hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu.
Selain itu, ada dana yang harus dikeluarkan untuk membeli tiket dan transpor, mungkin pula harus mengantre, dan sebagainya. Namun, menonton TV di rumah bisa dilakukan kapan saja secara gratis.
Selain itu, ada dana yang harus dikeluarkan untuk membeli tiket dan transpor, mungkin pula harus mengantre, dan sebagainya. Namun, menonton TV di rumah bisa dilakukan kapan saja secara gratis.
Dalam upaya membangun
budaya sensor mandiri di rumah, teman saya ada yang memilih “No TV” secara
total di rumah.
Ada juga yang memilih berlangganan TV kabel saja karena ada saluran khusus buat anak-anak. Ada pula yang memilih menyetel TV hanya pada jam-jam tertentu.
Ada juga yang memilih berlangganan TV kabel saja karena ada saluran khusus buat anak-anak. Ada pula yang memilih menyetel TV hanya pada jam-jam tertentu.
Saya sendiri bukan
termasuk yang “mengharamkan” tontonan di bioskop dan televisi. Bagi saya,
tontonan elektronik itu tidak melulu berpengaruh negatif. Pengaruh positifnya
pun ada.
Tetap ada televisi di
rumah saya. Namun, tidak semua acara boleh mereka tonton. Sinetron-sinetron
tertentu (tidak semua sinetron) yang menurut saya tidak baik untuk mereka,
masuk daftar yang tidak boleh ditonton.
Tidak terlalu sulit, sih,
karena saya sendiri memang kurang suka menonton sinetron.
Jika yang ditayangkan bermuatan pengetahuan
dan bernilai positif, yuuuk … nonton sama-sama sekalian untuk family time.
Misalnya tentang anak-anak
berprestasi di seluruh dunia, fakta unik binatang, atau fenomena alam yang
mengagumkan. Main "game online" yang edukatif bersama anak juga menyenangkan. Misalnya ZenCore Cara Seru Asah Otak.
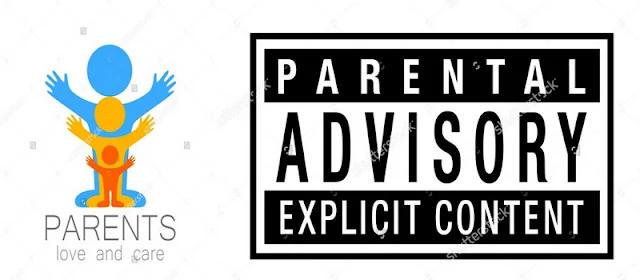 |
| Orangtua perlu menyeleksi tontonan. |
Budayakan Sensor Mandiri dari Rumah
Kasih sayang dan
kepedulian orangtua kepada anak bukan berarti dengan membiarkan mereka
melakukan segala yang mereka mau.
Dalam hal tontonan, menerapkan budaya sensor mandiri justru merupakan bentuk kepedulian orangtua kepada sang buah hati.
Dalam hal tontonan, menerapkan budaya sensor mandiri justru merupakan bentuk kepedulian orangtua kepada sang buah hati.
Dalam pandangan saya, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan untuk membangun budaya sensor mandiri ini.
1. Memberi teladan pada anak.
Anak adalah peniru ulung. Mereka akan cepat
belajar dari contoh. Jika orangtua tak ingin anak “menjadi tua” di depan TV,
hendaknya orangtua pun tidak menghabiskan waktu sepanjang hari dengan menonton
acara TV.
Perintah “Sana belajar! Jangan nonton
melulu!” akan kurang efektif jika orangtua terus saja asyik menonton sinetron
dengan volume keras.
2. Membatasi waktu dan jenis tontonan.
Sepakati bersama kapan boleh menonton dan
apa yang boleh ditonton. Sesuaikan dengan usia dan perkembangan kejiwaan
anak, bukan dengan keinginan anak
semata.
Mengajak anak ke bioskop dan menonton film
yang bukan untuk usianya, sebaiknya tidak dilakukan. Film yang sudah lolos
sensor LSF selalu diberi klasifikasi usia: Semua Umur (SU), 13+, 17+, dan 21+.
Klasifikasi usia itu tentu bukan asal-asalan disematkan. Salah satunya karena
ada adegan yang tidak sesuai untuk anak di bawah usia tersebut.
3. Mendampingi anak saat menonton.
Sedapat mungkin dampingi anak saat menonton
TV. Dengan begitu kita bisa tahu dan mengontrol apa yang mereka tonton. Jika
ada yang perlu dijelaskan, bisa langsung dijelaskan.
Film lawas The Gods Must Be Crazy yang beberapa kali ditayangkan di televisi termasuk
yang ditonton oleh anak saya.
Dengan mendampinginya menonton, saya dapat
memberi penjelasan kepada dia tentang perbedaan budaya dan alam Bostwana dengan
Indonesia, tentang kenapa Xixo dalam film tersebut berpakaian seperti itu.
4. Memperkaya wawasan anak.
Setelah menonton sebuah film atau acara
lain di TV, dorong anak untuk mencari tahu. Kita bisa memfasilitasinya dengan
menyediakan buku-buku bacaan yang sesuai. Atau bisa juga mencarinya
bersama-sama di internet.
Selesai menonton acara yang berseting luar negeri,
putra bungsu saya biasanya membuka buku tentang negara-negara di dunia.
Sebenarnya saya membeli buku itu untuk referensi saya. Tapi ternyata justru si
bungsu yang lebih sering membaca dan menikmati isinya. Tentang ini bisa dibaca lebih lanjut dalam Berliterasi Sejak dari Rumah.
Di tangan yang bijak, film dan tayangan elektronik lainnya bisa dimaksimalkan nilai positifnya. Bisa untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan hiburan sehat. Bisa pula untuk membangun kedekatan antar anggota keluarga.
Yuk, kita bangun budaya sensor
mandiri sebagai bentuk kepedulian dan sayang kita kepada anak. #AyoSensorMandiri
















Tidak ada komentar
Komentar dimoderasi dulu karena banyak spam. Terima kasih.